Tahu-tahu kampus bisa pegang WIUP.
Tahu-tahu ormas keagamaan juga.
Semuanya rapi diatur di revisi UU Minerba. Di atas kertas tulisannya tampak manis: “pemberdayaan”, “kemandirian ekonomi”, “peluang bagi UMKM, kampus, dan ormas”. Tapi ketika saya baca pelan-pelan, rasanya bukan lagi manis. Rasanya getir.
Logika resminya kira-kira begini: negara tidak sanggup lagi menanggung semua—kesejahteraan dosen, peneliti, pengelola kampus, pengurus ormas. Anggaran terbatas, kebutuhan banyak. Maka ditempuhlah jalan yang dianggap “kreatif’: silakan mencari nafkah sendiri lewat tambang. Negara tinggal bikin pasal, teken, lalu mundur pelan-pelan dari tanggung jawab utamanya.
Di brosur, mungkin kalimatnya begini : mandiri, inovatif, berdaya saing. Keren.
Di kepala saya, muncul pertanyaan lain: Bagaimana nasib daya kritis kampus kalau kampus ikut punya konsesi tambang?
Selama ini, dosen dan mahasiswa bisa bicara lantang soal kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan kriminalisasi warga. Suatu hari, mereka bisa berhadapan dengan kenyataan bahwa lubang tambang yang mereka kritik itu milik almamater sendiri.
Apakah kritik masih akan sekeras dulu? Atau mulai pelan, berbisik: “Tolong, jangan terlalu keras, ini menyangkut pendapatan kampus”
Mari bayangkan ruang diskusi di kampus.
Dulu: debat soal keadilan ekologis, hak warga, dan masa depan planet.
Nanti: debat soal berapa persen royaltyy yang masuk kas kampus.
Jika dulu yang diperdebatkan adalah nilai, nanti yang dihitung bisa jadi neraca. Kalau dulu mahasiswa menolak tambang, nanti mereka bisa diajak ikut “kunjungan lapangan” ke tambang milik sendiri—lengkap dengan helm proyek dan foto-foto untuk brosur kampus.
Di situlah letak bahaya halusnya. Revisi UU Minerba ini bisa menjadi cara elegan untuk menjinakkan kampus. Bukan lagi dengan membungkam secara frontal, tapi dengan cara yang lebih efektif yaitu mengajak kampus duduk di meja yang sama, makan dari piring yang sama.
Hal serupa juga mengintai ormas keagamaan.
Selama ini, ormas kerap menjadi tempat warga mengadu ketika berhadapan dengan aparat, perusahaan, dan kebijakan timpang. Maulai dari konflik agraria sampai dampak tambang. Di desa-desa, ketika tanah mulai digusur atau sungai tercemar, yang didatangi bukan hanya kantor bupati, melainkan juga rumah-rumah tokoh agama.
Kalau ormas keagamaan ikut memegang konsesi, posisi itu menjadi rumit.
Di satu sisi, mereka punya mandat moral.
Di sisi lain, mereka punya izin tambang.
Ketika warga datang mengadu karena terganggu tambang, mereka bisa berhadapan dengan pengurus yang duduk di dua kursi sekaligus: pembela umat, sekaligus pemilik usaha. Di titik itu, garis antara pembela dan pelaku bisa kabur.
Ironinya, semua ini terjadi ketika tata kelola tambang kita sendiri belum beres. Lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga, hutan yang terus berkurang, korban jiwa yang jatuh di sekitar area tambang, penegakan hukum yang lemah—daftarnya panjang.
Kalau memakai logika sehat, situasi seperti itu seharusnya dijawab dengan pengawasan yang lebih ketat, penindakan yang lebih tegas, dan penyaringan yang lebih selektif terhadap siapa yang boleh masuk ke bisnis tambang.
Yang dilakukan justru kebalikannya. Pintu dibuka lebih lebar, karpet baru digelar, aktor baru diajak masuk.
Kampus.
Ormas keagamaan.
Dua institusi yang mestinya berdiri di bagian paling depan dalam urusan akal sehat dan moral publik.
Sebagai orang yang menulis dari ruang redaksi, saya melihat langkah ini sebagai bentuk “cuci tangan” kelas berat. Negara seperti berkata: “Kami sudah bikin regulasi, kalian silakan urus sendiri hidup kalian. Kalau bisa dari tambang, lebih bagus lagi.”
Negara tak perlu terlalu repot memikirkan gaji dosen, dana penelitian, atau operasional ormas. Cukup sediakan pasal tentang WIUP, lempar izin, lalu biarkan kampus dan ormas bernegosiasi sendiri dengan batu bara, nikel, emas, dan seluruh isi perut bumi.
Masalahnya, tambang bukan soal angka di laporan keuangan belaka.
Tambang meninggalkan lubang.
Tambang memindahkan kampung.
Tambang bisa memindahkan garis pantai, bahkan garis hidup orang.
Saya tidak anti-kemandirian. Kampus memang perlu mandiri. Ormas pun perlu sumber daya. Tapi ketika kemandirian itu diserahkan kepada sektor yang paling banyak meninggalkan jejak luka ekologis dan sosial, kita wajar bertanya: ini kemandirian, atau jebakan?
Kalau ukuran keberhasilan kampus mulai dihitung dari seberapa besar produksinya di tambang, dan ukuran kekuatan ormas dihitung dari seberapa luas konsesinya, ada yang sedang bergeser di dasar republik ini.
Dan, supaya lengkap, mari kita bayangkan satu adegan tambahan—sedikit jenaka, tapi cukup menegangkan: Bagaimana kalau pola yang sama suatu hari diterapkan juga kepada pers?
Misalnya, persatuan organisasi pers diberi peluang yang sama: WIUP, izin tambang, konsesi sana-sini.
Republik ini tidak perlu lagi khawatir menghadapi kritik tajam atas kebijakan yang mengeruk perut bumi dan hutan. Tinggal berikan izin dan WIUP. Semua beres.
Tidak perlu repot konferensi pers.
Tidak perlu pusing menjawab laporan investigasi.
Wartawan bisa diajak sibuk mengawasi overburden dan produksi harian, bukan lagi mengawasi kekuasaan. Rubrik “Lingkungan” pelan-pelan berubah menjadi “Update Produksi”. Dan kalau ada warga protes soal tambang, liputannya bisa dipertimbangkan ulang: “Ini menyangkut sponsor utama, kawan”
Untungnya, skenario itu masih fiksi.
Masih.
Kalau tidak, mungkin suatu hari saya akan menulis opini ini bukan dari ruang redaksi, tapi dari site office di tepi lubang tambang—sambil pakai helm proyek, rompi oranye, dan tetap menulis: “Tenang, semua baik-baik saja.” (***)
Penulis : Nicky Saputra
Berita terkait :


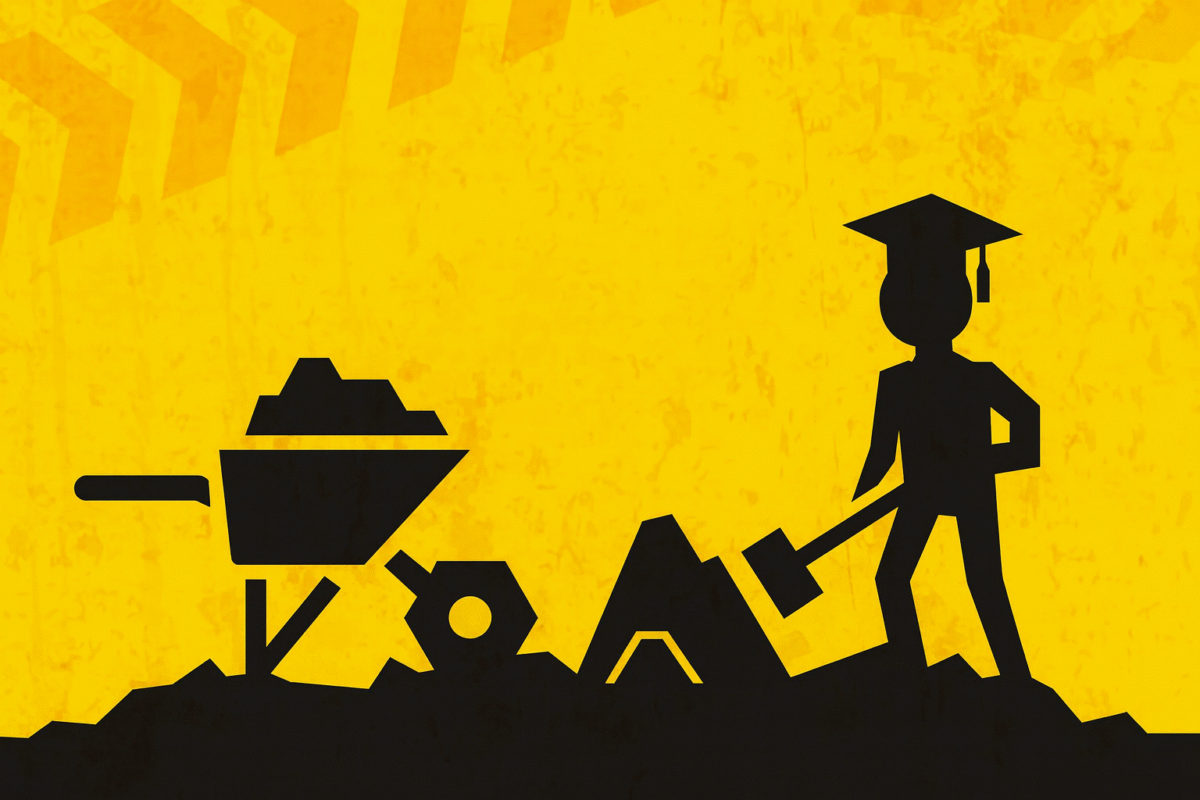 Ilustrasi. (redaktif.id)
Ilustrasi. (redaktif.id) 


